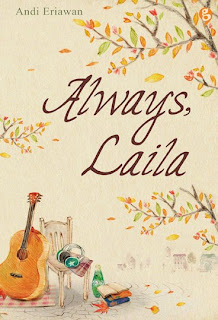Maafkan Kami, DR. Herry Suhardiyanto…
Kembali ke
Buitenzorg tidak seperti kembali ke
kotamu. Yang dicari tidak ada di sini. Yang dibayang-bayangkan tidak juga
muncul. Yang diharapkan, mengkhianati. Yang dicemaskan, terjadi.
“Di Rindu Alam
puncak, matahari terbitnya keren, Bung!! Dari parkiran mobilnya, kita bisa
lihat matahari muncul dari balik gunung.”
Begitu yang
dibilang teman saya, seorang dosen harapan masa depan. Seorang PNS Golongan
IIIA, tengah mengambil S2. Jujur dia punya sikap. Manis tutur katanya. Di
pundaknya kelak, bersandar nasib pendidikan negeri kita.
Sambil dipeluk
angin bersuhu teramat rendah, berangkatlah kami dari Bandung pada pagi buta.
Kokok ayam belum terdengar. Para bencong pun masih belum bubar. Mereka masih di
tengah misi. Dan dari kami bertiga tidak ada satu pun yang sudah mandi.
“Ini Bandung,
Bung. Dingin.”
Mobil dinas
ditancap gasnya sedemikian rupa. Satu persatu yang menghalangi, berhasil kami lewati. Tidak peduli itu bis
atau truk gandengan. Kami sedang mengejar terbitnya matahari.
Dalam satu
setengah jam, kami sudah berada di kawasan Puncak, Cianjur. Langit mulai terang
dan di arah timur sudah terlihat warna kemerahan. Mobil dinas pun semakin
dipaksa bekerja di batas maksimalnya.
“Mari kita
manfaatkan mobil dinas ini sebelum bapak saya pensiun dua tahun lagi.”
MenDikNas,
maafkan kami.
Tapi penyesalan
langsung pupus begitu saja sewaktu Restoran Rindu Alam terlihat oleh pandangan
mata. Masih ada 1-2 menit hingga matahari terbit, sepertinya. Mobil pun segera
menepi. Lalu…
Lalu…
Lalu…
“Sejak kapan
Rindu Alam pindah jadi menghadap ke arah barat, ya…”
Manusia bertenaga uap rokok
*adegan jangan ditiru*
Yah, dimaklumi.
Mungkin waktu itu teman saya ini tidak membawa kompas. Atau, dia keliru. Yang
dia lihat bukan sun rise, tapi sun tet.
Maka, setelah
menggerutu sejenak, perjalanan dilanjutkan menuju Buitenzorg. Cukup satu jam hingga kami tiba di kota.
Dan… Ya, ampun. Suasana pagi di sana sungguh mengerikan.
Macet panjang, terutama di jalur menuju Jakarta. Dan jumlah angkotnya sangat
mendominasi jalan aspal. Seakan-akan, jalan dibangun memang diperuntukkan bagi
mereka sahaja.
“Ini bukan kota
hujan. Ini kota angkot. Atau, dulu pernah hujan angkot.”
Begitu yang
dijelaskan teman saya. Karena pelancongan sebelumnya dilakukan pada malam hari,
kali ini si dosen mulai menjelaskan satu persatu tiap sudut Buitenzorg.
“McD di sini
lebih murah daripada di Bandung.”
“Ada dua terminal
angkot yang saling berdekatan. Satu milik kotamadya, satu milik kabupaten.”
“Jalan lubang dan
becek seperti ini biasa, Bung. Jangan protes. Di depan masih banyak lagi.”
“Itu warung baso
paling enak di Buitenzorg. Catat: di Buitenzorg.”
”Polisi di sini
baik-baik. Naik motor tanpa
helm ngga akan ditilang. Yang ngga boleh, jalan kaki di atas trotoar sambil
pakai helm. Disangka ngejek, ntar.”
Pemandangan di
luar jendela tidak menarik minat kami. Tapi, tidak apa. Toh, tujuan utama
perjalanan ini adalah mengabadikan kampus IPB yang rimbun oleh pepohonan.
Terbayang oleh kami hutan semi tropis yang masih perawan dan jalan setapak
penghubung antar gedung kuliah di sana. Beserta penghuninya, tentu saja.
Penghuni yang
manis, tentu saja. Jenis perempuannya, tentu saja. Tapi, tidak akan kami
apa-apakan, tentu saja. Tidak berani, tentu saja.
Menjelang pukul
tujuh pagi, kami memasuki pintu gerbang kampus. Bayar seribu rupiah untuk
parkir mobil, lalu…
Pagi di Institut Pertanian Buitenzorg. Cahaya matahari malu-malu di sini.
Mereka menyebutnya danau
Jalan setapak menuju Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
“Suka ada orang
gila duduk-duduk di sini kalau saya lewat. Saya bertahan selama ini dengan
memikirkan bahwa orang gila itu ialah sebenarnya artis sinetron… yang seksi…
seksi sekali… sangat seksi sekali… Ya, betul-betul seksi sekali…”
Keluhan pertama
kami di kampus ini adalah sulitnya mencari kantin yang nyaman untuk sekedar
minum jus atau ngopi. Juga kantin yang menyediakan asbak. Jadilah kami si turis
lokal mengotori lantai dengan abu dan puntung rokok.
Rektor IPB,
maafkan.
Tapi, penyesalan
justru kembali berubah menjadi keluhan dan gerutuan sewaktu kami mulai
menyusuri kampus dengan berjalan kaki. Manis di awal, getir di akhir. Mirip
bait lagu kau yang memulai kau yang mengakhiri.
Sementara teman
saya si dosen mengikuti kuliah, pada pukul sembilan, berdua kami berjalan kaki
di jalan utama kampus. Tidak butuh mobil agar bebas masuk keluar hutan.
Atau kebon, tepatnya?
Di sepanjang
jalan, sesekali kami melirik hutan di sisi kanan. Sesekali kami masuk, dan
tidak lama keluar lagi karena medan yang terlalu berbahaya. Juga karena sayang
sepatu saya baru. T-shirt saya baru. Jaket saya baru. Baru dibeli semalam.
Begitu juga yang dikenakan teman saya.
Padahal, masih
lama menuju lebaran.
Ini kami sudah
berjalan lebih dari satu kilometer, tapi tidak ada lagi yang menarik untuk
dipotret. Udaranya tidak
ramah, cukup gerah. Keringat bercucuran, banyak nyamuk dan kami tidak tahu
jalan di hadapan kami menuju ke mana.
Khawatir
tersesat, kami pun mengambil langkah bijaksana, yaitu kembali ke parkiran. Dengan mobil, sekali lagi berputar. Dan…
parkir di tempat lain, lalu berjalan kaki lagi. Dan… panasnya. Gerahnya. Mampir
sebentar ke sebuah kantin untuk minum.
“Apa???!! Tidak
jual Teh Botol????”
Pilihan pun jatuh
pada, konon, itu jus jeruk dan alpukat. Dan… kembali ke mobil, parkir di tempat
semula. Dan… menggerutu.
Sudah pukul
sebelas, si dosen belum muncul juga. Kami mencoba bersabar.
Tunggu sebentar. Saya lagi Facebook-an…
Itu pesan pendek
dari teman saya si dosen yang sedang menempuh beasiswa menimba ilmu S2 di IPB.
Buitenzorg, 04 April 2009