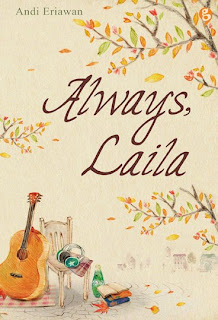Satu Milyar Duapuluh Satu
Adalah waktu itu tengah malam di bukit
Sukawana. Berempat kami membangun sebuah tenda dom, menghangatkan tubuh di
sekeliling api unggun sambil memanggang sosis yang ditusuk ranting cemara. Di
belakang kami, bayang gelap Gunung Burangrang dan Tangkuban Perahu. Di hadapan,
terhampar kerlip lampu kota Bandung
Botolnya botol
saos.
Sementara langit,
terlalu banyak yang dapat diceritakan tentangnya. Seperti bintik jerawat di
wajah kamu, langit malam ditaburi semilyar duapuluh dua bintang. Baru usai saya
hitung semua, satu persatu. Lalu kembali mengulangnya dari awal. Kali ini
masing-masing bintang saya beri nama.
Dan bulan, di
manakah engkau berada?
Begitu saya
bertanya dalam hati. Lupa, jika saat itu adalah akhir bulan. Pantas saja dompet
terasa tipis sekali di pantat saya.
Acara berkemah
yang sungguh membosankan mengingat tidak ada satu pun yang membawa gitar.
Apalagi harmonika. Tapi, sekalipun seseorang membawa harmonika, tidak ada
satupun diantara kami yang bisa memainkannya. Jangankan meniup harmonika,
bersiul saja kami sumbang.
Setelah usai
memberi nama pada bintang-bintang di langit (tentu, saya beri nama kamu pada
yang paling terang), seseorang akhirnya membuka suara.
Yaitu, saya
sendiri.
“Menurut kalian,
apa yang paling menarik di dunia ini?”
.
.
.
Tak ada yang
menjawab. Diam semua. Ada yang terlihat begitu mengantuk, membiarkan sosis
panggangannya hangus hitam. Satu orang melamun, memandang ke arah semilyar
duapuluh satu bintang (iya, sudah saya simpan satu untuk kamu sebagai oleh-oleh
pulang). Mungkin sedang memikirkan pacarnya. Mungkin selingkuhannya. Dan ada
yang duduk berjongkok memunggungi kami, menghadapkan tubuhnya ke arah gunung.
Sama-sama melamun. Atau, sedang pundung?
Sepertinya,
pertanyaan saya tentang hal yang paling menarik di dunia ini sama sekali tidak
menarik bagi mereka. Tak tega diri ini mengganggu keasyikan masing-masing.
Tapi, setelah dipikir ulang, lebih baik tega daripada bengong.
“Kamu,” kata saya
pada teman nomor satu sambil menunjuk ke arah wajahnya menggunakan sosis
hangus, “lakukan sesuatu untuk menghibur kita semua.”
Tak lama kemudian, area
api unggun ini berubah menjadi panggung hiburan.
“Untuk menghibur
hati yang murung, ijinkanlah saya menyumbangkan sebuah lagu.”
Teman nomor satu
ini memang punya suara yang mumpuni. Merdu sangat. Juga khas. Nafasnya pun amat
kuat. Jika beliau menyanyi, burung-burung pun akan diam khidmad medengarkan.
Daun-daun berguguran, tak kuasa menahan berat suaranya. Lalu air mata kita akan
mengalir tanpa terasa. Dan ingatan pun terbang menuju berbagai peristiwa.
Kekasih yang pergi, keluarga yang ditinggalkan, serta gaduh seisi rumah saat
merayakan lebaran.
Sudah beberapa
kali dia menjuarai Festival Bintang Radio dan Televisi. Tawaran untuk masuk ke
dapur rekaman bukannya tidak pernah datang, tapi justru sebaliknya. Ia tolak
satu persatu setiap kontrak yang disodorkan.
“Saya cuma
ingin berduet. Dan saya menunggu pasangan yang benar-benar tepat.”
Dan suasana di
bukit Sukawana menjadi syahdu sewaktu beliau membawakan Perfect Day. Mata kami
mulai basah di Merepih Alam. Lalu, kerinduan pada ayah menjadi menggebu sewaktu
beliau mendendangkan lagu Daddy. Terpaksa saya menghentikannya sebelum kami
semua ingin cepat-cepat pulang ke rumah dan memeluk ayah kami.
“Berikutnya,”
kata saya pada teman nomor dua yang kedapatan sedang menyeka air mata.
Tahu benar bahwa
saya tidak suka menunggu, teman saya mengeluarkan sesuatu dari tasnya: sebuah
saklar. Dia berdiri, sebentar membersihkan tanah di pantat, lalu menghadap ke
arah hamparan kota. Bibirnya tersenyum, kini. Tersenyum simpul. Tapi dia
sungguh keliru jika mengira manis senyumannya. Namun demikian, itu sungguh
senyum yang sangat misterius dan membuat penasaran.
“Lihat,” dia
bilang.
Tombol saklar pun
ditekan. Terdengar suara klik, dan satu-persatu lampu kota Bandung dan
sekitarnya padam. Jutaan lampu padam. Padam tak bersisa. Dibuatnya Bandung
gelap gulita. Juga Cimahi, Soreang dan Kabupaten Bandung Barat. Juga Banjaran.
Juga Ujungberung. Juga Jatinangor.
Juga rumah kamu.
“Belum selesai,”
katanya lagi, seakan masih ada kejutan lain.
Suara klik
kembali terdengar. Tapi tidak ada sesuatu yang terjadi. Kami tidak melihat ada
perubahan sesuatu apa.
“Lihat ke arah
timur.”
Serta merta kami
bertiga menggerakkan kepala. Tapi dasar mereka yang tidak terbiasa dengan mata
angin, maka pandangan mereka berbeda-beda arahnya. Ada yang ke atas ke bawah.
Dan ada yang ke semak-semak. Hanya saya, dan cuma saya yang mengarahkan
pandangan dengan benar. Cuma saya yang tahu bagaimana menentukan arah timur di
malam hari dengan benar. Karena sangat mudah. Amat mudah.
Untuk menentukan
di mana itu timur, kamu cukup dengan mengetahui arah barat terlebih dahulu.
Lalu, putar tubuhmu dengan sudut 180 derajat celcius.
Dan di sana, di
arah timur sana, samar-samar saya melihat sebuah lampu menyala, menerangi
sebuah rumah. Hanya satu, lain tidak.
Saya tahu pemilik
rumah itu. Rumah pacarnya.
Sungguh menarik.
Menarik sekali. Lain waktu akan saya pinjam saklar tersebut. Akan saya padamkan
lampu rumah kamu. Ya, hanya rumah kamu. Lalu saya datang ke sana dengan membawa
sebatang lilin dan senter. Lalu kita berdua akan candle light dinner.
Setelah meminta teman
saya, yang dicurigai adalah anak Direktur PLN, mengembalikan lampu-lampu kota
ke sedia kala, saya menunjuk teman nomor tiga.
“Giliran kamu.
Berceritalah.”
Nah, teman satu
ini rajanya mendongeng. Beliau punya koleksi dongeng klasik yang nyaris tak
terbatas. Dari manca negara. Berbagai daerah. Maka, dimulailah cerita nasib
buruk tukang celup yang terkenal itu.
Alkisah,
seorang pencuri sedang beraksi. Mengendap-endap ia pada atap sebuah rumah yang
diincarnya. Dasar nasib buruk, atap rumah tersebut tiba-tiba roboh, tidak kuat
menahan beban tubuhnya. Ia pun jatuh dan mati.
Anggota
keluarga si pencuri tidak menerima kejadian tersebut, lalu menuntut si pemilik
rumah ke pengadilan. Alasannya: Gara-gara atap rumah yang tidak kuat, saudara/
ayah/ putera/ menantu kami meninggal dunia. Sang hakim yang adil mengabulkan
tuntutannya, menjatuhkan hukuman gantung sampai mati pada si pemilik rumah.
Tapi si
pemilik rumah membela diri.
“Bukan salah
saya, Pak Hakim.Ini salah tukang kayu yang membuat atap. Dia yang membuat atap
rumah saya tidak kuat.”
Maka sang hakim pun memanggil tukang kayu dan menjatuhkan hukuman mati padanya. Tapi si tukang kayu membela diri.
“Ini salah si
janda tetangga saya yang berbaju hijau, Pak Hakim. Gara-gara baju hijaunya yang
menyala, perhatian saya terbagi sewaktu membuat atap rumah.”
Maka sang
hakim memanggil si janda dan menjatuhkan hukuman mati padanya. Si janda pun
membela diri.
“Ini salah tukang celup, Pak Hakim. Saya meminta baju saya dicelup warna
coklat, jadinya malah hijau muda.”
Maka tukang
celup pun dipanggil. Tidak bisa membela diri, sang hakim menjatuhkan hukuman
mati pada si tukang celup dengan cara digantung. Seorang algojo ditugaskan
untuk melaksanakan eksekusi. Tapi dasar algojo, tiang gantungannya terlalu
pendek bagi si tukang celup yang bertubuh tinggi itu. Akibatnya, meski tali
gantungan sudah melingkar di leher, tapi tukang celup tidak mati-mati juga.
Lalu sang algojo melaporkan masalah tersebut pada sang hakim.
Kata hakim,
“Bodoh kamu. Cari saja tukang celup pendek.”
Maka, seorang
tukang celup bertubuh pendek pun ditangkap dan dihukum gantung sampai mati.
Sebuah dongeng
pengantar tidur yang sangat ciamik. Kami berempat mimpi indah malam itu. Senyum
tipis menyungging di masing-masing wajah kami.
“Camping,
the art of getting closer to nature while getting farther away from the nearest cold beverage, hot shower and flush toilet.”
[Anonymous]
Bukit Sukawana, 17
Juni 2007