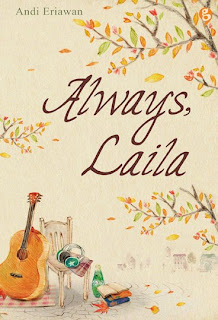Pointilisme
“Di permukaan bulan sana,
saya tuliskan nama kita
dengan deretan abjad-abjadnya
yang tersusun rapi.
Semoga
abadi.”
Demikian saya
merayu. Kalimat terakhir saya bisikkan dengan lembut disertai ketukan yang
terpadu.
Memandang tidak
percaya, perempuan itu merogoh isi tasnya, lalu mengeluarkan sebuah teropong
bintang dan mengarahkannya pada bulan. Ia selidiki kata-kata saya dengan
mengintip dari celah lensa, memastikan sendiri apakah saya sedang berbual atau
sungguh-sungguh.
Tersenyum, dia,
tidak lama kemudian.
Aih.
“Tapi, Andi,
tidak ada yang abadi, bukan, kecuali Dia?”
Aih, lagi.
“Tentu saja. Yang
saya maksud adalah… tiga-empat puluh tahun ke depan.”
“Kamu akan keburu
tua sewaktu merasa menyesal atas keputusan itu.”
“Selama hidup
nyaris tiga puluh tahun di permukaan bumi, saya tidak pernah menyesali segala
sesuatu. Kecuali perbuatan dosa, tentu,” kata saya tanpa nada ragu.
“Tapi, Andi…”
“Kamu banyak
ber-tapi,” potong saya di kuali. “Kalau terlalu banyak tapi, setiap kisah dan
dongeng tidak akan pernah berlanjut. Diam dia menggantung tak ke mana-mana.”
“Betul. Saya
setuju. Namun…”
Nah. Demikianlah
jika kamu berhubungan dengan mereka yang senang menggunakan kata tapi dan
namun. Usaha apa pun yang kamu lakukan untuk meyakinkan mereka adalah percuma.
“Sayangnya…”
Untuk menghadapi
mereka, kamu jangan pernah memberi penjelasan. Jangan memberikan argumen.
Dengarkan saja sampai akhir. Anggukkan kepala, mengirimkan isyarat setuju.
Pura-pura, tentu.
“Hanya saja…”
Lalu, ketika kamu
berpikir bahwa kamu tinggal menuruti saja apa yang mereka inginkan, ya, kamu
salah lagi. Karena mereka sendiri pun tidak tahu apa yang mereka inginkan.
Keinginan mereka abstrak. Hanya seniman yang bisa mengerti. Seniman aliran
abstrak atau surealis.
Saya bukan.
Bandung, 13 Mei 2009