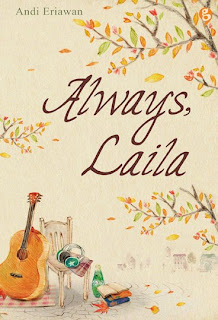Terbaik
Ada sebuah
kejadian lewat yang masih saja hinggap di benak saya. Menclok seperti burung
kakak tua, tak pernah mau pergi. Agak sedikit mengganggu, sebenarnya. Membuat
saya sering melamun sewaktu menyetrika kemeja kerja. Membuang sia-sia air dalam
gayung sewaktu mandi. Salah menyuapi sendok nasi ke hidung sewaktu sarapan.
Keliru turun dari bis menuju kantor. Sampai-sampai, kadang saya dibuat lupa
pakai celana. Tak ada yang melihat, untungnya.
Hebat kan saya,
masih saja merasa beruntung?
Kejadian itu
adalah sebuah reuni kecil-kecilan kelas kami di masa SMA. Tepat tahun lalu.
Salah satu dari mereka yang hadir adalah seorang mantan pacar. Perempuan,
tentunya, sedang hamil tujuh bulan untuk yang kedua kali. Datang pula sang
suami si pelaku penghamilan.
“Kenapa belum menikah juga?”
Begitu si ibu
hamil yang sekaligus mantan pacar di masa lalu itu bertanya pada saya dengan
lugas dan ringan. Seperti bertanya, apa saya sudah makan? Atau, sehat-sehat
saja?
Saya sungguh
tidak mengerti, jawaban seperti apa yang beliau harapkan. Apakah beliau tidak
tahu bahwa untuk menikah itu dibutuhkan dua pihak. Pihak laki-laki dan pihak
perempuan. Dengan demikian, sepatutnya pertanyaan tersebut dilemparkan tidak
hanya pada saya seorang.
“Mungkin karena doa kamu.”
Begitu dia
menebak. Menuduh. Menyudutkan. Menyalahkan satu pihak saja. Tapi, saya tidak
mengerti maksud dia punya tebak-tebakan.
“Maksudnya, kamu berdoa untuk diberikan yang
terbaik, kan? Yang terbaik.”
“Tentu saja.”
Begitu saya
menjawab dengan cepat. Padahal, saya masih tidak mengerti maksud beliau ke arah
mana. Tapi, saya mencium adanya bau-bau jebakan di sini. Pasti.
“Nah, mungkin karena itulah kenapa kamu belum
menikah juga. Kamu ingin yang terbaik, sih. Jadi, Tuhan akan kasih kamu yang
terbaik. Masalahnya…”
Tuh, kan, ada
masalah.
“Masalahnya, si perempuan yang hendak dipasangkan
dengan kamu, dia pun berdoa kepada Tuhan agar diberikan yang terbaik. Dan…
sungguh tidak adil jika kamu adalah orangnya.”
Dan saya pun
menangkap nada mengejek dari kalimat itu.
“Coba kamu berdoa agar diberikan yang… lumayan.
Atau, cukup baik. Toh, kamu juga ngga baik-baik amat.”
Pada mulanya,
saya agak kesulitan mencerna apa yang dia sampaikan. Padahal, usus saya sangat
kuat dalam mencerna daging kerbau sekalipun. Bahkan, baru-baru ini, saya tidak
mengalami masalah apa-apa sewaktu melahap durian lengkap dengan kulitnya.
Setelah berpikir
sejenak, merenung di ujung seperti benteng catur, ada pesan mulia dan nasihat
berharga pada kalimat-kalimatnya yang berhasil saya tangkap. Memang, sejak saya
mengenal beliau, nyaris tidak pernah saya temukan hal tercela yang dia lakukan.
Beliau seorang perempuan soleh-solehah. Setiap kali mengingatnya, maka secara
otomatis kita akan mengambil air wudlu. Kalaupun ada cela dari beliau, mungkin
hanya satu, yaitu dahulu mau berpacaran dengan saya, yang tentunya seorang
laki-laki yang tidak baik-baik amat (menurut istilah dia).
Tapi, saya
lumayan, lah.
Iya, kan, Bu
Ustadzah?
Bandung, 25 Mei 2009