Surat untuk Bunda
Ada kabar gembira dari puteramu ini, Bunda. Atas berkat doamu, aku telah diterima kerja. Setelah duapuluh lima tahun engkau urusi, tiba waktunya bagi si manja ini memberi sesuatu untukmu dari gaji pertamanya. Tidak. Aku tidak akan memberitahu apa itu. Biarlah ini menjadi sebuah kejutan manis menjelang hari lebaran saat aku pulang nanti.
Tapi kebahagiaan kita tidak hanya sampai di situ. Tuhan telah bermurah hati mempertemukan aku dengan calon menantumu. Memang, ia tidak secantik Bunda di masa muda dahulu. Maafkan pula jika perempuan ini belum pandai memasak, Bunda, apalagi mengaji. Ia belum bisa menakar garam dan gula, juga membedakan huruf ”ba” dan ”ta”. Namun, percayalah, ia seorang yang istimewa.
Bunda pasti bertanya-tanya tentang siapakah dia dan berharap agar aku segera menceritakannya. Tapi aku justru kebingungan untuk memulai dari mana. Jika kumulai dari namanya, Bunda tentu akan bertanya anak siapa. Jika kuberi tahu usianya, pertanyaan Bunda akan berlanjut pada asal kampungnya.Yang aku khawatirkan, halaman kertas dan tinta ini habis sebelum sempat kusampaikan salam dan doa untuk Bunda. Karena itu, kuharap Bunda tidak kecewa, kali ini hanya akan kuceritakan bagaimana kami berdua berjumpa.
Segalanya berawal dari kecintaan kami pada gunung, Bunda. Rimbunnya, hijaunya, segarnya, bisikannya di malam hari dan pelukannya saat terlelap mimpi. Juga rasa cinta kami pada pantai, Bunda. Aroma garam, pohon kelapa, serta debur ombak yang begitu memikat. Atau sekedar memperhatikan terbitnya matahari secara perlahan dari batas horisontal. Karena itulah, Bunda pasti dapat dengan mudah menebak di mana calon menantumu menemukan puteramu.
Tidak. Pertemuan kami bukan terjadi di gunung, Bunda. Di sana terlalu sunyi dan sepi. Gunung bukan tempat yang tepat untuk menemukan pasangan, tapi justru untuk menyendiri. Berfikir tentang masa depan dan mengevaluasi hal-hal yang telah dilakukan.
Bukan juga pantai, Bunda, mengingat di sana terlalu ramai. Aku biasanya lebih sibuk berenang hingga kulitku merah terbakar daripada berkenalan. Lagipula, rasanya sulit menilai seorang gadis yang akan Bunda sayangi di balik pakaian pantai mereka yang basah dan minim.
Ya, benar, Bunda. Tuhan mempertemukan kami di sebuah ruang praktik dokter gigi yang sederhana, tempat yang Bunda hampir tidak pernah berhasil membawaku ke sana waktu aku kecil. Saat itu tiga bulan yang lalu ketika gigi geraham terakhirku tumbuh. Meski banyak orang bilang bahwa ini adalah salah satu tanda puteramu menjadi dewasa, tapi rasa sakitnya tak tertahankan. Luar biasa. Bahkan aku hampir menangis, mengepak barang memutuskan untuk pulang.
Untungnya, Bunda, aku kehabisan tiket kereta. Daripada menunggu delapan jam untuk jadwal berikutnya dalam kondisi tersika, aku memutuskan untuk ke dokter gigi saja. Di sanalah aku ditemukan olehnya.
Tepat sekali, Bunda. Calon menantumu itu sama seperti aku, seorang pasien yang tengah didera siksa akibat gigi bungsu yang muncul dengan tidak sempurna. Mungkin karena rahang kami sama-sama tidak memiliki tempat yang cukup untuk si bungsu tumbuh dengan wajar. Itu yang dokter kami bilang.
Terbayangkah olehmu, Bunda, perbincangan pertama kami berdua? Dimulai dengan suara ”a i u” yang tidak jelas, apapun yang ia ucapkan membuat tekanan darah justru naik ke atas. Tapi keakraban kemudian tumbuh seiring dengan kesembuhan kami. Pertemuan tidak hanya terjadi di ruang praktik, tapi juga sewaktu kami difoto dan menebus obat di apotik.
Hari demi hari, kami mulai mengerti satu sama lain, membicarakan hal-hal menarik yang terlintas di kepala. Mulanya pertemanan ini biasa saja, tanpa bujuk rayu dan embel-embel ini-itu. Sampai suatu hari, baru menyadari kelebihannya. Dia menanyakan tentang engkau, Bunda!
Sulit bagiku untuk merangkai kata-kata yang tepat untuk menggambarkan sosok Bunda. Jika kumulai dari caramu membesarkan, maka dia akan bertanya orang mana. Kalau kuceritakan bahwa Bunda paling juara dalam memasak rendang, takutnya aku ditanya apa resepnya. Seringkali kesempatan kami yang singkat untuk bertemu itu dipisahkan oleh larutnya malam karena asyik menceritakanmu.
Tidak sampai di situ. Tepat hari kemarin, dia berkata bahwa suatu hari ingin bertemu denganmu, Bunda. Mulanya aku hanya terdiam atau memberi jawaban penuh teka-teki padanya. Tapi permohonannya terdengar tulus, didasarkan pada kekagumannya pada Bunda. Karena tidak mau terlalu lama membuatnya menunggu, akhirnya kujawab juga pertanyaannya dengan jawaban yang sangat pahit terdengar di telingaku. Bahkan setahun lewat pun kalimat itu nyaris tidak pernah bisa aku ucapkan.
”Bunda sudah meninggal.”
Entah karena rasa empati yang besar, atau karena menangkap perubahan air wajahku, tapi aku sungguh sangat menyukai cara dia berikutnya (dan mungkin hal tersebut yang membulatkan keputusan untuk menjadikannya menantumu). Dia terdiam, memandangku sesaat. Tangannya mencengkeram lembut bahuku. Perlahan, kulihat matanya berkaca-kaca, lalu air mata menitik.
Bunda, puteramu yang dahulu manja, kini telah dewasa. Ia akan segera pulang, beserta oleh-oleh dan menantu untukmu.
Bandung,
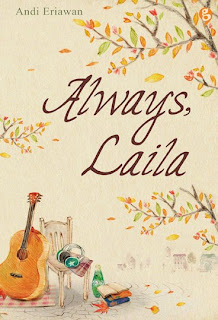

Comments