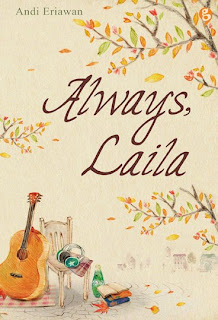Bulan Madu
Pada awalnya,
tidak ada rencana untuk melakukan perjalanan menuju Kampung Pacet, Bandung
Coret. Sementara di mana itu letaknya Pacet, hanya segelintir orang yang tahu. Dan saya, a.k.a Andi Eriawan, termasuk
dari si segelintir tersebut. Sungguh beruntung. Patut dibanggakan dan layak
mendapatkan penghargaan.
Tak ada jalan
tak macet menuju Pacet.
Demikian pepatah
yang beredar. Dan sayalah yang menyebarkan pepatah tersebut. Bagaimana lagi,
untuk sampai ke Pacet, kita harus melewati jalur-jalur yang perawan macet.
Macet oleh motor, angkot, bus dan truk. Ada Jalan Buah Batu yang sulit ditembus
atau Dayeuh Kolot yang berjalan kaki saja kita akan mengalami kesulitan. Belum
lagi perbaikan jalan di kawasan Banjaran dan Bale Endah yang tak pernah usai.
Jika perjalanan dilakukan pada hari libur, maka akan ada tambahan volume
kendaraan luar biasa dari berbagai daerah menuju dan keluar kota Bandung. Belum
lagi pesta khitanan atau perkawinan dari rumah-rumah di pinggir jalan akan
semakin memeriahkan suasana.
Namun, setelah
lolos dari kemacetan, perjalanan menjadi terasa amat sangat menyenangkan.
Bahkan luar biasa. Pohon-pohon si peneduh tumbuh rapat di kanan dan kiri
sepanjang Ciparay. Lalu kamu akan menemukan jalanan berkelok, menanjak dan
sesekali tak beraspal. Ada sawah, ada gunung, dan bening sungai Citarum.
Kemudian perkebunan bawang daun, seledri dan stroberi terhampar di lereng
pebukitan. Jangan tanya temperatur udaranya bagaimana. Siang hari sangat panas,
mirip di California atau Texas. Tapi, di pagi dan sore terasa dingin sekali,
mirip di Kentucky.
Atau, McD.
“Itu Gunung
Rakutak.”
Begitu kata si
penumpang yang sedari tadi duduk setia di belakang, menunjuk si gunung
bersejarah di mana ribuan orang pernah melakukan pagar betis yang menentukan
arah negeri ini.
“Dan itu saung
milik mama,” tambahnya lagi, menunjuk ke arah sebuah bukit di seberang.
Kami menepi dan
turun di halaman sebuah warung bambu. Pura-pura membeli Oreo dan Kue Kipas,
padahal sesungguhnya hendak menitipkan motor barang sepuluh-duapuluh menit.
Padahal,
tigapuluh menit.
Padahal, kami
tidak saling kenal.
Di atas bukit
sana, terlihat sebuah saung yang mampu menampung dua keluarga untuk menikmati
nasi timbel plus ikan mas bakar, atau sekedar berasyik-masyuk dengan pasangan
sambil menelanjangi hamparan kebun stroberi dan pegunungan di sekelilingnya.
Juga terdapat
kolam ikan yang belum ber-ikan. Bunga-bunga yang belum berbunga. Mushala yang
belum dilengkapi tempat berwudlu. Dan kandang besar peternakan ayam negeri yang
baru usai dipanen minggu lalu.
“Aku ingin berbulan madu di sini.”
Begitu kata anak
si pemilik tempat tersebut.
“Aku? Bukan… kita?”
Tanya saya.
Dalam hati, tapi.
Pacet, 18 Agustus 2009